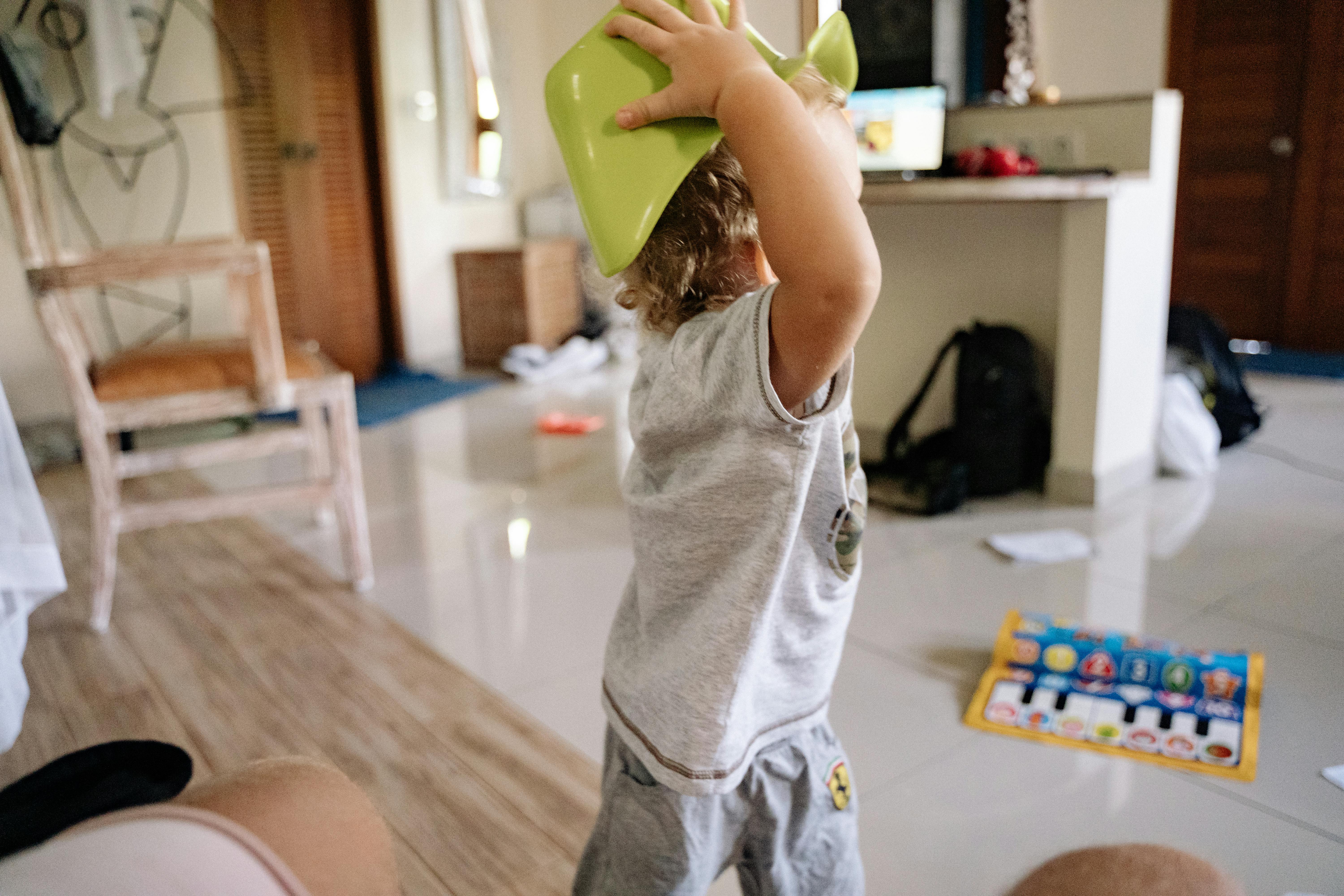Rabu, 17 Desember 2025
Budaya Berpikir Masyarakat Desa
Senin, 01 Desember 2025
Sudah Ada Bahan di Alam, Kreatifitas yang Tidak Ada
Memunculkan kreatifitas ternyata susah.
Saya selalu kagum kepada bangsa yang bisa mengubah alam liar menjadi peradaban yang maju. Mereka datang dari tempat yang jauh ke tempat yang tak tersentuh. Awalnya daerah hutan belantara, bertahun-tahun kemudian berubah menjadi kota. Bagaimana caranya semua itu bisa terjadi?
Menurut Napoleon Hill, semua yang terjadi di dunia ini berawal dari pikiran manusia. Saya pun merasa jika perubahan yang terjadi berawal dari dalam pikiran. Masalahnya, bagaimanakah seharusnya kita berpikir agar peradaban itu bisa terwujud? Bagaimanakah seharusnya kita berpikir agar lanskap yang semula tak tersentuh manusia kini menjadi sumber kehidupan yang bermanfaat?
Apakah ada hubungannya antara sikap inferior warga desa dengan kreatifitas yang tumpul?
Sebelum kreatifitas muncul, seharusnya kita bertanya kepada diri sendiri, "apa tujuan hidup kita di dunia?" Jika pertanyaan demikian terlalu luas untuk sebuah jawaban, maka kita turunkan dengan menjawab pertanyaan, "apa tujuan hidup kita di desa?"
Saya setuju jika ada orang yang bilang apabila tujuan hidup penting.
Tidak selamanya kesempatan datang, kadangkala harus diciptakan. Tidak selalu hidup bisa mengalir begitu saja, mengikuti arus kalau ternyata arus tidak cukup deras untuk membawa kita ke muara. Andaikan saat ini kita sedang berada dalam sebuah perahu, tepat di tengah sungai yang berarus deras maka cukup yakin akan sampai di muara impian. Namun, bagaimana jadinya jika saat ini tak ada arus yang membawa untuk sampai di muara?
Tentu saja harus berpikir bagaimana caranya perahu bisa melaju. Entah menggunakan dayung atau mesin tempel.
Tidak ada alasan untuk menerapkan filsafat fatalisme di tengah abad 21 yang penuh tentangan. Filsafat nerimo atau terima nasib ini meredupkan gairah, menghancurkan ambisi. Selanjutnya, mendatangkan kemalasan untuk berpikir.
Saya merasakan sendiri, jika kemiskinan bisa membuat orang enggan untuk mengubah diri. Seakan strata sosial yang diembannya sebuah kutukan yang tak mau diubah. Masalahnya, bukan sekedar jumlah harta yang tak bertambah tetapi sikap toleransi terhadap kemalasan dan keengganan untuk menata diri. Seakan-seakan orang miskin boleh hidup berantakan, compang-camping, dan hidup tanpa aturan. Orang miskin terlanjur menerima cap jelek sejak masa kolonial.
Tidak perlu penelitian untuk bagaimana cara berpikir orang miskin. Keluarga kami bagian dari sekian juta orang miskin di Indonesia. Entah apa kriteria orang miskin menurut Badan Pusat Statistik, pokoknya keluarga saya dilabeli miskin. Namun, bukan berarti menjadi orang yang enggan untuk berpikir.
Ingat, kemiskinan bukan berarti alasan bagi kemalasan untuk berpikir.
Anak-anak harus disekolahkan, bagaimana keadaan ekonomi keluarganya. Alasan yang bisa diterima jika bersekolah sebagai cara untuk keluar dari jerat kemiskinan. Sayang, hal demikian tidak selalu berhasil. Ada banyak hambatan--selain pendidikan--apabila lingkaran kemiskinan susah terentaskan. Lantas, pada akhirnya diserahkan kepada setiap individu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
Kata orang, sekolah bisa mengasah ketajaman berpikir seseorang. Sayang, siswa yang dijejali hafalan malah menumpulkan pikiran. Orang demikian tidak terangsang untuk berpikir. Bagi mereka, belajar adalah suatu proses yang membosankan bukannya menyenangkan. Saya pun mengira jika kebosanan inilah yang membuat kreativitas tidak muncul ke permukaan. Katanya, kegiatan yang berulang dan membosankan bisa membuat orang tidak kreatif. Tidak terangsang untuk melakukan sesuatu yang baru. Begitu pula keadaan yang begitu tenang tanpa rangsangan.
Sekolah telah usai dilaksanakan, kini berdiri menatap tepat di bingkai pintu. Apa yang harus dilakukan? Berdiam diri saja atau melakukan sesuatu, tentu dengan sebuah tujuan.
Jika kamu melihat sekeliling, alam pedesaan gitu meninabobokan. Justru berbanding terbaik dari penjelajah yang tadi saya bicarakan, melihat alam liar seakan sebuah potensi besar yang harus dioptimalkan kebermanfaatannya.
Kalau orang kreatifitas itulah yang melihat sesuatu yang tampak tidak berguna atau setidaknya terlihat biasa saja akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pada fase inilah kreativitas sangat dibutuhkan. Saya pikir tidak bisa kalau alam hanya dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sekali lagi, seharusnya alam merangsang manusia untuk berpikir. Kalau bukan alam, lantas siapa yang merangsang manusia untuk berpikir?
Sabtu, 22 November 2025
Menyambut Jalan Tol Getaci
 |
| Gambar: Antara via Pikiran Rakyat |
Rabu, 12 November 2025
Terikat dengan Tanah
Padang rumput yang hijau di musim panas dihiasi oleh kawanan domba berbulu putih dan belang-belang. Kawanan itu hanya diawasi oleh satu atau dua orang saja. Tidak jauh dari tempat si ternak merumput, ada sebuah ger berbahan kulit ternak. Di sampingnya, ada seorang wanita yang sedang memasak. Tampak asap mengepul ke udara membentuk garis putih di sela hijaunya padang rumput dan langit yang biru cerah.
Saya tidak sedang menceritakan lanskap Mongolia yang indah. Mari kita cermati bagaimana perilaku bangsa nomaden Mongolia yang tidak memiliki kebiasaan mengolah tanah. Sebuah bangsa yang terkenal haus akan petualangan serta pengalaman menjelajahi dunia baru. Menganggap jika menetap bisa satu tempat terasa membosankan. Atau, gairah untuk mencari suasana baru memang lebih besar dibandingkan menikmati apa yang telah ada dalam waktu lama.
Saya pun merasa jika kaum nomaden melihat kehidupan hanya sementara. Tak ada pembangunan untuk menyongsong masa depan. Tak ada hak atas tanah, semua yang terhampar di dunia adalah milik bersama. Tak ada batas wilayah sehingga apa yang mereka lihat di hadapannya adalah sesuatu yang layak untuk dimiliki; bila perlu dengan dirampas.
Saya selalu takjub dengan budaya orang Mongolia. Mereka bisa hidup di tanah yang bersuhu ekstrem. Kala musim dingin tiba mereka kedinginan begitu pula ternak-ternaknya. Mungkin itulah alasan kenapa mereka berpindah-pindah.Sebuah bangsa nomaden, tidak menetap untuk mengolah lahan. Timbul pertanyaan, "kenapa mereka tidak seperti kami yang menetap di suatu wilayah? Kenapa mereka tidak membajak sawah? Apakah semata alasan musim yang berganti?"
Kami harus mengolah tanah, menanaminya dengan padi, kemudian menunggu waktu panen. Membutuhkan waktu yang lama dari mulai ditanam hingga waktu panen. Sebuah masa menunggu yang membosankan, terkadang.
Bagi petani menetap, tidak ada pikiran untuk bersikap agresif. Berbeda dengan bangsa peternak nomaden. Sepanjang sejarah, suku-suku bangsa peternak menunjukkan sifat-sifat yang agresif. Hal itu dapat dimengerti, karena mereka secara terus menerus harus menjaga keamanan beratus-ratus binatang ternak terhadap serangan atau pencurian dari kelompok-kelompok tetangga. Kecuali itu, karena mereka perlu makanan lain di samping daging susu, dan keju. Hanya saja, makan lain tersebut seperti gandum dan sayur perlu diperoleh dari suku bangsa lain yang hidup bercocok tanam. Maka tidak ada persoalan kalau mereka dapat tukar menukar atau berdagang tetapi biasanya berusaha mendapatkan makanan itu dengan menguasai dan menjajah bangsa yang hidup dari bercocok tanam.
Tidak semua orang harus menjadi pengembara.
Bagi suku pengembara, tanah bukanlah benda yang harus dijaga. Bagi suku yang suka bermukim maka tanah adalah segalanya. Dari tanah dia dilahirkan kemudian akan kembali ke tanah, suatu hari nanti. Bagi suku pengembara tanah adalah hamparan. Bagi suku yang bermukim tanah adalah modal. Kami bisa saling membunuh karena masalah tanah. Namun, kami bisa merelakan hewan ternak yang mati atau dicuri orang. Tak ada niat untuk balas dendam.
Berbeda dengan bangsa nomaden benda tak bergerak adalah harta yang lebih utama. Di tengah padang pasir yang tandus unta begitu berguna. Jika ada yang mencuri maka besok lusa akan kembali dicuri. Bila perlu ditambah jumlahnya.
Saya pun berpikir jika kata ikatan kepada tanah masih ada kaitannya dengan genetik. Masih ada pula kaitannya dengan cara berpikir seseorang. Sedikit filsafat hidup ditambah kebutuhan mendesak yang tidak mungkin terelakkan. Mari kita berpikir sederhana, jika suku pengembara harus terikat dengan tanah maka akan sulit bagi mereka menggiring ternak atau membawa rumah-rumah sementara (tenda atau ger). Sedangkan suku pemukim, rumah pun dibuat permanen tertancap langsung ke dalam tanah dan memang hindari terpaan angin. Lagi pula rumah-rumah dibuat kokoh untuk menyimpan hasil panen.
Keterikatan dengan tanah adalah bentuk cinta
Rasa memiliki dan identitas: Tempat tinggal sering kali menjadi bagian integral dari identitas seseorang. Merasa terikat dengan tempat tersebut dapat mencerminkan rasa aman, akar, dan koneksi pribadi yang mendalam, yang mirip dengan esensi cinta.
Dalam beberapa budaya, kembali ke tanah kelahiran merupakan bentuk keharusan. Tanah tempat dulu bermain bersama kawan. Tanah tempat dulu menggembala anak kerbau sementara induknya digunakan untuk membajak sawah. Sebuah masa yng indah.
Hal yang wajar jika timbul kerinduan keada hamparan tanah yang dulu terbiasa untuk ditapaki oleh kaki-kaki kecil. Juga kemarahan ketika tanah leluhur berubah fungsi menjadi kawasan industri pemilik kapital. Sama seperti rasa cinta kepada sesama manusia, keterikatan manusia akan tanah memang lumrah. Bukan sesuatu yang dibuat-buat semata untuk nostalgia. Ikatan batin dengan tanah merupakan bentuk lain dari mekanisme manusia untuk bertahan hidup.
Andaikan seorang manusia enggan untuk memperhatikan tanah serta keberlanjutannya, sama saja seperti keengganan untuk merawat tubuhnya sendiri. Mengolah, memupuk, menjaga, hingga mewariskan tanah merupakan bagian dari realita budaya. Semuanya tak akan hilang selama manusia memiliki rasa untuk berkasih sayang.
_____________________
Sumber rujukan:
John Man, Jenghis Khan (Legenda Sang Penakluk dari Mongolia), Alvabet, Jakarta: (2008)
Kuntjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta: (1986)
Sejarah Nama-nama Temat di Bandung, e-Book daring, diakses 12 Nopember 2025
Minggu, 26 Oktober 2025
Obrolan Warga Desa
 |
| Foto: Hartono Subagio via www.pexels.com |
Sebuah kejadian yang berulang, apabila ada saudara atau tetangga--kebetulan banyak pula tetangga masih ada ikatan saudara--yang datang ke rumah. Tanpa ditanya tak dinyana, mereka yang tiba langsung membuka obrolan. Topik pembicaraan ringan.
"Eh, tahu nggak sih, si Fulan tuh begini-begitu."
Kami yang sedang menikmati tontonan televisi, lantas tak bisa mengelak untuk memperhatikan pertanyaan.
Maka terjadilah obrolan keseharian yang sudah bisa ditebak akhirnya.
Begitulah, banyak orang di sekitar saya enggan untuk membicarakan perihal abstrak. Apabila membicarakan sesuatu yang belum pernah dicerap oleh indera, maka mereka ramai-ramai untuk menolak.
Kultur kami, seakan membangun dinding yang tebal dengan dunia luar. Kalau Anda membayangkan bénténg berbahan batu di abad pertengahan, tebal kan? Mungkin setebal itu pemisah antara kami dengan dunia luar. Tentu bukan pemisah secara fisik, tetapi pemisah mental.
Kultur kami yang menutup diri terhadap informasi cukup mengejutkan saya ketika beranjak dewasa. Agak percuma jika teknologi informasi semacam televisi hadir ke tengah-tengah rumah. Toh, embaran yang tergambar di sana tidak dianggap berharga.
Padahal, ketika sekolah dulu, saya senantiasa diajak untuk mengenal bagian lain dari dunia. Oleh guru, kami diharuskan untuk tahu nama-nama negara di berbagai benua. Kami pun diajari sejarah bagaimana negara tersebut bisa terbentuk atau kembali runtuh. Namun, sayangnya tidak semua murid menganggap jika pengetahuan akan dunia luas layak dijadikan bahan obrolan.
Kecuali, khusus empat keponakan saya yang masih usia belia. Mereka begitu tertarik berbicara tentang dunia di luar apa yang terindera. Terkadang membicarakan nama hewan khas Afrika, suku bangsa di Malaysia, atau artis Korea yang mereka suka.
Memperhatikan ini, sepertinya saya menemukan sebuah pola.
Ada orang-orang yang enggan berbicara tentang hal di luar keseharian. Sebaliknya, ada orang-orang yang tertarik dengan hal di luar keseharian. Setidaknya, dua tipe manusia ini mesti dihadapi dengan cara yang berbeda. Tipe pertama, saya hanya berusaha untuk mendengarkan sembari berusaha agar tidak menyela obrolan. Orang-orang seperti ini hanya butuh untuk didengarkan. Malahan, jika kita beri tanggapan, bisa jadi mereka tersinggung. Tipe kedua, orang-orang yang membutuhkan kawan bicara untuk menerawang ke lain dunia. Mereka memang tertarik dengan dunia luar, penasaran dengan apa yang terjadi di sana, tanggapi obrolan berdasarkan topik yang disampaikan.
Jadi, kalau pagi-pagi buta ada saudara yang ingin bicara banyak untuk sekedar menyampaikan pengalaman, cukup perhatikan. Apabila keponakan tertarik untuk membicarakan tontonan, ajak mereka untuk masuk ke dalam dunia yang tak tersentuh tangan tersebut. Dengan begitu, selalu ada interaksi serta komunikasi di antara kami.
Ngobrol nggak penting, yang penting ngobrol.
Minggu, 28 September 2025
Terhubung dengan Ruang di Pedesaan
Manusia désa senantiasa terhubung dengan manusia désa lainnya. Sayangnya, kita sering lupa untuk terhubung dengan ruang.
Ada banyak alasan kenapa hal demikian terjadi. Bisa jadi, sikap guyub bukan hadir karena alasan kemanusiaan. Sikap guyub warga sekedar keinginan untuk diperhatikan oleh manusia lain. Manusia désa semata menjadi kumpulan warga-warga yang berdomisili dalam satu kawasan. Padahal, keterhubungan kita terjadi karena adanya ikatan batiniah sesama makhluk Tuhan.
Saya curiga, jika sesungguhnya manusia désa pun individualis. Kita menjalin hubungan semata karena ada kepentingan. Andaikan tetangga dan saudara tidak bisa memberikan timbal balik, mungkin saja sikap guyub itu pun sirna. Kita merasa dekat bersama orang-orang yang memberikan kita kenyamanan. Apabila orang-orang terdekat kita tidak memberikan kenyamanan, masih maukah kita hidup berdampingan?
Nah, fokus perhatian seseorang kepada orang lainnya inilah yang mengesampingkan perhatian kepada ruang.
Contoh klasik, perkara membuang sampah sembarangan. Hal demikian timbul karena warga tidak peduli dengan ruang sekitar. Tidak ada perasaan terhubung dengan benda-benda tak bernyawa yang tidak bisa memberikan "timbal-balik" nan nyata. Batu, tanah, dan pohon jelas berbeda dengan manusia karena mereka tidak bisa memuji kita tatkala meraih prestasi. Benda-benda itu tidak akan memberikan angpao andaikan lebaran tiba. Konsep balas budi benda mati tidak gamblang sebagaimana manusia yang memiliki kesadaran.
Sesaat setelah bangun pagi, tidaklah terpikir jika hari yang akan kita arungi bukan hanya berusaha untuk memenuhi ambisi pribadi. Kamar, rumah, pemukiman, jalan raya, tempat bekerja, hingga selokan yang terlihat oleh bola mata adalah bagian dari hidup. Ada hubungan saling ketergantungan satu sama lain. Sikap tidak peduli, tidak layak ada dalam hati.
Di desa, bukan hanya tempat berkumpulnya warga. Desa pun terdiri dari ruang yang mesti terjaga.
Perlakuan kita terhadap ruang yang melingkupi tidaklah sama dengan perlakuan dengan sesama manusia. Orang-orang menjadi sosok yang seharusnya dihormati. Begitupula ruang, sesuatu yang harus dihormati. Dinding di rumah, memberi kita naungan. Bunga yang mekar memberi kita kesegaran penglihatan. Lantas, kenapa tidak diperlakukan selayaknya memperlakukan orang yang kita sayang?
Bagi saya, ruang menjadi tempat untuk berkontemplasi dan berkreasi.
Pikiran senantiasa terisi oleh informasi penting yang berhubungan dengan ruang. Seekor semut yang berjalan beriringan di ranting pohon, memberi kita sebuah penanda tentang betapa pentingnya keberadaan mereka. Sekawanan burung yang berkicau kala pagi memberitahu warga jika peran mereka sangatlah berharga. Membutuhkan cara khusus untuk menjaga serta melestarikan eksistensinya. Dengan begitu, kita senantiasa disandarkan jika peran manusia di dunia sangatlah menentukan keberlangsungan.
Kenyataannya, pikiran manusia yang mempengaruhi bagaimana ruang terbentuk. Apakah ruangan akan tampak acak-acakan atau rapih, tergantung bagaimana kita memandang ruang sekitar.
Entah kenapa perkara ruang dan kecerdasan ruang (spasial) ini tidak memperoleh perhatian khusus. Anak-anak akan dipuji serta ditinggikan kedudukannya ketika pintar menyelesaikan ujian negara dengan nilai tinggi. Namun, anak-anak tidak pernah diberikan apresiasi ketika pintar menata. Bahkan, kegiatan menata sekedar perkara rumah tangga yang dianggap terlampau biasa. Menata tidak lagi suatu bagian dari budaya yang mesti diberi penghargaan tinggi.
Suatu bangsa yang pandai menata ternyata sekumpulan manusia yang mampu menghargai ruang. Mereka senantiasa menganggap jika keterhubungan dengan ruang menjadi bagian dari budaya yang mesti dijunjung tinggi. Andaikan ruang bukan sesuatu yang penting, bisa dimengerti apabila rumah hingga sebuah kota tampak berantakan serta tidak nyaman untuk dijadikan hunian.
Memperhatikan ruang bukanlah harus mengerti akan dunia dan seisinya. Ada banyak elemen sederhana yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Saya selalu terpukau kepada budaya Cina yang senantiasa memperhatikan elemen-elemen kehidupan. Entah abstrak atau kongkrit, semuanya dianggap penting. Bagi manusia yang mengagumkan logika, perhatian akan elemen-elemen tersebut hanya dianggap mitos kuno. Namun, kenyataannya pemikiran sederhana manusia berbudaya mampu membuat kemajuan sekaligus kelestarian.
Ketika budaya lama mulai ditinggalkan, tidak usah heran sering terjadi kekecewaan. Ternyata, sesuatu yang baru tidak selalu layak ditiru.
Minggu, 13 Juli 2025
Merambah Lahan Digital
Di desa kami, lahan pertanian mulai sempit. Tentu saja bukan tanahnya yang berkurang, kini wajah désa berubah setelah ada pembangunan pemukiman dan pabrik. Bagi mereka yang masih bergantung pada sektor pertanian, maka dianggap sebagai sebuah ancaman.
Seberapa serius ancaman itu, saya sendiri belum meneliti. Perlu ada ahli yang menentukan seberapa besar ancaman yang dimaksud. Atau, sebaliknya ini dianggap sebagai sebuah peluang?
Sudah diramalkan sejak bertahun-tahun sebelumnya jika wajah désa kami akan berubah menjadi areal industri. Bertani hanya menjadi profesi penopang ketika sektor industri belum bisa dijadikan sumber pendapatan utama. Meskipun euforia industrialisasi itu senantiasa ada, belum tentu menjadi sektor yang tetap kokoh di tengah terpaan dinamika global.
Sebagaimana diketahui, perubahan haluan pembangunan di desa bisa terjadi lantaran ada kebutuhan yang mendesak. Karena berbagai penyebab, maka industri membawa angin segar bagi mereka yang tidak kebagian lahan pekerjaan. Hanya saja, kelemahan sektor industri adalah tidak senantiasa sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Terkadang, pabrik tidak membutuhkan banyak orang sebagaimana lahan pertanian.
Lantas, ke manakah kami harus mencari?
Saya pikir, lahan digital bisa menjadi pilihan. Tidak membutuhkan dana besar untuk membeli lahan yang lebih luas. Tidak perlu pula warga mengurus lahan agar tetap subur.
Memang bukan perkara mudah jika mengalihkan petani tanah menjadi petani digital. Akan ada banyak kendala jika mengajak warga yang terbiasa memegang benda nyata untuk beralih memegang benda yang tak tersentuh. Saya melihat sendiri betapa kedua bidang ini bisa membingungkan orang-orang yang terkaget-kaget dengan perubahan zaman. Sejujurnya, kami tidak siap menghadapi problematika zaman yang susah diterka.
Kita mulai dari mengetahui cara berpikir para petani. Mungkin ini cara termudah dan paling mendasar, menurut saya pribadi. Apabila kita mengamati, petani terbiasa menanam bibit di lahan, menunggu hingga sampai di masa panen. Pemeliharaan pun seputar menyiangi gulma dan pemupukan secara berkala. Selebihnya, hanya menunggu waktu.
Saya merasa jika pola pikir ini belum hilang, dan tak akan hilang. Masalahnya, ketika masuk ranah digital maka cara berpikir seperti ini tidak cocok diterapkan.
Dalam perspektif petani, lahan merupakan hamparan bukan sesuatu yang tidak kelihatan. Sedangkan benda yang bersifat digital tidak pernah tergambar apalagi terhampar jika pikiran kita tidak ikut serta untuk berimajinasi.
Bercocok tanam di tegal memang berbeda jika dibandingkan dengan bercocok tanam di lahan digital. Apabila sebutir biji padi ditimbun oleh lumpur sawah maka besar kemungkinan dia akan tumbuh dengan sendirinya. Namun, berinvestasi di "tanah" digital membutuhkan pengelolaan dan pemeliharaan yang lebih intensif. Dengan kata lain, warga harus senantiasa berpikir bukan hanya membiarkan konten digital begitu saja sambil berharap akan berbulir dan berbuah.
Lahan digital merupakan realitas baru. Tidak ada sejak zaman penjajah dulu, tidak bisa pula seorang petani membuka buku sejarah dalam rangka untuk belajar. Dengan kata lain, pengalaman saja tidak cukup ketika seorang warga desa diharuskan menjajaki réalitas virtual.
Lahan digital bukan hanya tentang mengunggah konten di media sosial. Meskipun itulah salah satunya, masuk ke ranah virtual sebaiknya memiliki sifat mendambakan kebaruan. Hal-hal baru yang tidak mudah tercipta di dunia nyata maka dunia maya bisa menjadi saluran. Dengan kata lain, cara berpikir abstrak lebih dominan dibandingkan dengan berpikir kongkrit.
Sayangnya, kemampuan berpikir abstrak tidak terasah apabila kita senantiasa bersentuhan dengan aspek kongkrit. Manusia yang terbiasa bekerja dengan pola berulang bisa kesulitan diajak berpikir abstrak. Belajar pun tidak cukup dengan mengamati, mencoba kemudian mengulangi hingga mahir. Realitas virtual tampaknya tidak suka pengulangan.
Mari kita mulai dari hal sederhana. Menulis isi pikiran kita di internet, saya pikir bisa menjadi pintu masuk untuk menjelajah ke dunia maya yang lebih luas.
Senin, 23 Juni 2025
Urbanisasi yang Didorong oleh Tradisi
"Aa, ulin atuh ka kota!" saran seorang guru sekolah saya ketika berkunjung ke rumah.
Saya pun menanggapi anjuran itu hanya dengan sebuah senyuman. Tidak ada untaian kata yang terucap dari mulut. Meskipun tahu jika kalimat dari Bu Guru terucap setelah melihat saya tidak pergi ke kota sebagaimana pemuda desa lainnya. Ungkapan tidak segera ditanggapi karena dalam pikiran ada banyak opsi untuk disampaikan sebagai jawaban. Bingung pula mesti menyampaikan pilihan kata yang mana.
Opsi pertama, saya akan memberikan alasan kenapa masih berada di desa karena tidak tahu jika urbanisasi adalah sebuah tradisi. Saya pikir pergi ke kota hanyalah kebutuhan belaka. Andaikan seorang manusia tidak terdesak untuk pergi ke kota maka melangkahkan kaki meninggalkan désa bukanlah sebuah perkara yang wajib.
Opsi kedua, saya akan menyampaikan alasan keberadaan di desa karena keadaan keluarga mengharuskan tetap berada di rumah. Artinya, setiap keluarga memiliki situasi yang tidak sama. Bahkan, apabila dua keluarga bertetangga maka kami pun memiliki pilihan berbeda.
Opsi ketiga, saya punya kegiatan yang bisa dijadikan sumber kehidupan di desa. Bukanlah sesuatu yang besar tetapi harus dilestarikan karena pemberian Yang Maha Kuasa. Apabila dibiarkan begitu saja maka saya bisa dihantui rasa tidak bersyukur atas karunia yang telah diberi.
 |
| Sumber: ChatGPT |
Senin, 16 Juni 2025
Memanfaatkan Benda-benda Sederhana, Kenapa Orang Desa Enggan Melakukannya?
 |
| Botol bekas menjadi hiasan (Dokpri.) |
Rabu, 04 Juni 2025
Mempertahankan dan Memanfaatkan Bekal Hidup yang Sederhana
 |
| Dokumen pribadi. |
Sejak masa kanak-kanak, keluarga kami terbiasa memelihara kawanan domba. Kegunaan hewan berbulu ini sungguhlah besar bagi kehidupan keluarga. Selain kegunaan secara fisik, ternyata domba memiliki pengaruh yang kuat dalam kesehatan mental.
Sebagaimana yang pernah ditulis sebelumnya, domba-domba ini bisa menghasilkan daging yang nikmat juga menghasilkan pupuk kandang yang menyuburkan tanah. Andaikan tidak ada kotoran hewan, kami bisa kesulitan mencari solusi untuk kembali meningkatkan unsur hara di tanah. Sawah-sawah yang telah digunakan dalam waktu lama mengalami penurunan tingkat kesuburan. Telapak kaki saya pun merasakan betapa keras postur tanah yang sudah jenuh. Hamparan lahan di pedesaan perlu peremajaan.
Ketika domba digiring ke pengembalaan, ada pemandangan yang menyejukkan perasaan. Sesuatu yang akan sulit kami peroleh andaikan terpaksa meninggalkan kampung halaman. Terlebih, perkotaan di negeri kami tidaklah senyaman kota-kota di Eropa sana. Tidak ada jaminan jika akan ada taman luas dan sungai yang berair jernih sebagai penyejuk mata. Berdasarkan berita yang diterima, kota-kota besar malah menyuguhkan masalah mendasar bagi kehidupan ummat manusia.
Sampai hari ini, tidak ada kriteria yang bisa menentukan apakah domba-domba itu harus ditinggalkan atau dilestarikan. Saya pun kebingungan. Satu-satunya kriteria hanyalah faktor kedekatan.
Saya terbiasa "menyentuh" sesuatu yang dekat. Langka sekali bersegera untuk mencari yang jauh. Sudah lama tidak melangkahkan kaki hingga ratusan kilometer semata demi mencari harta lebih dari apa yang dimiliki hari ini. Alasannya, simpel saja. Hal-hal yang terdekat pun perlu untuk ditangani, dan tidak pernah ada waktu untuk berhenti walaupun cuma sehari.
Tanpa terasa, waktu telah berlalu begitu lama. Andaikan kami berpikir jika semua ini hanya percuma maka akan kecewa. Tidak ada yang luar biasa sebagai hasilnya. Namun, ada pemikiran sederhana yang mendasari keseharian di sini. Kami harus mensyukuri apa yang dimiliki hari ini.
Bersyukur bukan tentang menengadahkan tangan sambil berkata alhamdulillah. Bersyukur pun berarti membuat domba-domba ini tetap lestari.
-
Saya ini tipe orang yang langka bicara. Ada alasannya, obrolan warga begitu sering mengangkat topik yang tidak menarik. Tentu saja saya pun ...
-
Dalam belajar, kita ikuti filosofi pohon. Seperti pohon, kita awali belajar dengan pelajaran dasar layaknya akar. Akar itu kuat m...
-
Perencanaan sosial ( social planning ) pada dewasa ini menjadi ciri yang umum bagi masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami perubahan...


.png)